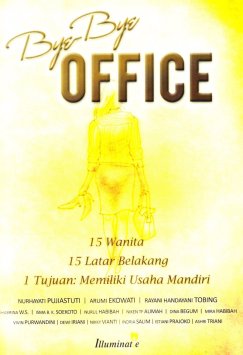 “Jadi beneran, nih, mau mengundurkan diri?” tanya atasan baruku ketika itu. Aku sudah memperkirakan reaksinya ini. Wajahnya menyiratkan keterkejutan, sementara tangannya masih memegang erat surat pengunduran diriku. Aku mengangguk mantap.
“Jadi beneran, nih, mau mengundurkan diri?” tanya atasan baruku ketika itu. Aku sudah memperkirakan reaksinya ini. Wajahnya menyiratkan keterkejutan, sementara tangannya masih memegang erat surat pengunduran diriku. Aku mengangguk mantap.
“Tapi mengapa, Mbak? Apa tidak sayang, mengundurkan diri setelah bekerja sekian lama? Apa tidak menunggu sampai pensiun saja, toh tinggal beberapa tahun lagi? Apalagi yang Mbak cari?”
“Kemerdekaan.”
Atasanku itu menatapku aneh setelah mendengar jawabanku. Baginya tidak masuk akal bahwa seorang pekerja berniat meninggalkan segala kelebihan sebuah perusahaan multinasional hanya untuk mencari kemerdekaan, padahal di luar sana masih banyak orang mendambakan jabatanku itu.
Tetapi, memang benar, kemerdekaanlah yang kucari. Selama bekerja di perusahaan itu, aku memang merasa bahagia. Suasana kerjanya menyenangkan, teman-teman kantor baik-baik semuanya, fasilitas bagus, gaji tidak jelek. Di perusahaan tersebut, cukup banyak ilmu yang kudapatkan selama hampir seperempat abad bekerja.
Tetapi di situ aku tidak mendapatkan kebebasan. Aku harus berangkat pagi-pagi sekali agar tidak ketinggalan jemputan dan begitu sampai di rumah, hari sudah gelap. Belum lagi kalau kena macet. Aku tidak bebas ke mana-mana kalau siang karena terikat jam kerja, apalagi kantor tersebut jauh di pinggir kota. Susahnya transportasi membuatku kesulitan kalau suatu ketika ingin mengurus masalah pribadi. Kalau harus lembur, hatiku kebat-kebit, siap-siap menghadapi wajah masam di rumah.
Aku ingin mempunyai pekerjaan yang memungkinkanku bebas mengatur jam kerjaku, boleh mengatur sendiri hari liburku tanpa harus deg-degan kalau-kalau permohonan cutiku ditolak. Aku ingin selalu dekat dengan keluarga, tidak perlu lembur, boleh menolak pekerjaan kalau sedang tidak ingin bekerja dan hanya mengerjakan pekerjaan yang kusukai. Dan tentunya, hmm, memuaskan bagi dompetku, kendati aku tidak harus kejar setoran lagi mengingat anak-anakku sudah besar.
Jauh sebelum aku mengajukan pensiun dini, sebetulnya aku sudah merintis pekerjaan yang kuinginkan itu.
Menjadi penerjemah.
Awalnya aku melihat iklan di sebuah mingguan wanita, bahwa sebuah penerbit ternama di kotaku mencari penerjemah novel. Iseng-iseng aku melamar. Selanjutnya aku diberi tes yang dikirim lewat faks, dan hasilnya harus kukirim lewat faks juga. Maklum, waktu itu internet belum merupakan kebutuhan vital seperti sekarang ini. Sebulan kemudian aku dikabari bahwa aku lulus tes, dan diminta datang ke penerbit itu. Disana, aku ditemui Manajer Produksi yang kemudian mengajariku pokok-pokok menjadi penerjemah yang baik. Setelah itu aku disodori satu dus besar yang berisi puluhan novel dalam bahasa Inggris, dan aku boleh memilih mana saja yang kusukai untuk kuterjemahkan. Aku boleh menyerahkan hasilnya kapan saja, asalkan tidak terlalu lama. Nah, ini dia. Keinginanku terpenuhi: aku boleh memilih yang kusukai; aku boleh bekerja kapan saja di rumah, cukup setiap Sabtu dan Minggu.
Buku pertamaku itu roman Harlequin, berjudul Man of Ice. Kalau sekarang, banyak temanku yang berteriak pahit … pahit … pahit … setiap mendengar kata Harlequin – tanda mereka agak jijik dan akan menolak mentah-mentah jika disodori novel roman sejenis itu. Tapi bagiku waktu itu, wah itu sudah hebat sekali. Apalagi setelah novel itu terbit dan aku melihat namaku tertulis di situ sebagai penerjemah, bukan main bangganya.
Rate? Tenggat?
Sebagai pendatang baru, waktu itu aku belum mengenal kedua kata kunci itu. Aku juga belum memusingkan kepuasan dompet, karena kebutuhan tersebut masih dicukupi dengan melimpah dari perusahaan tempatku bekerja.
Lama-lama tidak hanya Harlequin yang dipercayakan kepadaku, tetapi juga novel-novel dari genre lain. Aku berkenalan dengan penerbit-penerbit lain, mendapat pengalaman-pengalaman lain, bahkan ada yang memintaku untuk menyunting. Selanjutnya langkahku tidak kubatasi di dalam negeri, tetapi juga merambah pasaran internasional.
Pengalaman pertamaku sebagai penyunting membuatku terheran-heran. Sebelumnya, aku hanya berurusan dengan hasil terjemahanku, dan kalau kucocokkan kembali dengan bukuku yang sudah terbit, biasanya bedanya tidak jauh-jauh amat, bahkan belakangan makin lama koreksiannya semakin sedikit. Jadi aku tercengang sewaktu melihat dalam bahan yang kusunting itu terdapat kalimat-kalimat yang ajaib, penerjemahan kata per kata, melabrak idiom, bahasa yang kaku, sebagian jelas-jelas produk Google Translate bahkan ada yang kualitasnya lebih rendah daripada itu, seperti pengertian yang terbalik dan sebagainya.
Aku hanya bisa geleng-geleng kepala karena ternyata ada penerjemah yang belum bisa menggunakan tanda baca dengan benar. Kalimat yang sebenarnya sederhana, setelah diterjemahkan justru menjadi semakin sulit dimengerti karena si penerjemah salah memahaminya.
Dari situ aku mengambil kesimpulan bahwa tidak semua orang bisa menerjemahkan dengan baik. Seorang penerjemah yang terbiasa menerjemahkan dokumen yang berupa angka-angka, ilmu pasti, teknik dan semacamnya bisa mati kutu jika menerjemahkan novel. Sebaliknya, yang terbiasa menerjemahkan novel terkadang menjadi boros dalam pemilihan kata-kata, atau tidak menyadari bahwa penerjemahan dokumen tidak jarang menuntut konsistensi dalam penggunaan kata-kata.
Namun semua orang tentunya mengalami proses belajar itu, kan? Setiap penulis harus menguasai seluk beluk bahasa sumber (kalau bagiku, ini Bahasa Inggris), dan bahasa sasaran (bagiku ini Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa), termasuk di antaranya menguasai tata bahasa, idiom, cara penulisan dan sebagainya. Dalam menerjemahkan, aku betul-betul memperhatikan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Sampai sekarang, jika ragu tentang cara penulisan ini aku masih melihat panduan EYD dari buku-buku yang mudah sekali didapatkan di toko-toko buku, atau di situs Wikipedia.
Namun untuk menghasilkan suatu karya yang bagus, masih banyak proses yang harus dilalui. Aku selalu menambahkan “riset”, “manajemen waktu”, dan “memperluas jaringan” dalam hal wajib yang ada dalam “to-do-list”-ku.
Penulis atau penerjemah yang baik menurutku memang harus rajin melakukan riset. Dari pengalamanku selama ini, riset sangatlah membantu penerjemah memahami keseluruhan isi buku yang harus diterjemahkan. Pada waktu aku menerjemahkan buku ‘Desiree’ karangan Annemarie Selinko, misalnya, hampir setiap hari aku membaca hal-hal yang berhubungan dengan sejarah Prancis, terutama sekitar era Napoleon Bonaparte, sehingga setelah menerjemahkan buku itu aku menjadi paham tentang kondisi waktu itu. Aku juga rajin mendengarkan lagu kebangsaan Prancis La Marseillaise yang menjadi nafas dalam novel tersebut, agar dapat menangkap suasananya.
Manajemen waktu yang baik juga harus dimiliki setiap penerjemah. Ini penting, sebab penerjemah juga manusia yang mempunyai kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat. Penerjemah harus mengurus rumah, mengantar anak sekolah, ikut arisan, menghadiri pertemuan orang tua murid, pergi ke bank dsb. Sering terjadi, job datang secara bersamaan atau berturutan, dengan tenggat yang pendek atau saling berdekatan satu sama lain. Jika tidak pandai mengatur waktu, jelas bisa pusing sendiri, apalagi jika memiliki klien di luar negeri yang memiliki perbedaan waktu cukup besar. Tidak jarang klien yang berdomisili di Amerika Serikat mengajak rapat pada tengah malam atau dini hari lewat skype atau sarana internet lain.
Urusan memperluas jaringan ini juga masuk dalam catatan wajib yang menurutku harus dilakukan. Banyak cara yang bisa dilakukan penerjemah, seperti bergabung dengan mailing list (milis) penerjemah berbahasa Indonesia terbaik saat ini – Bahtera. Ketika aku bergabung dalam milis yang sangat aktif ini, ternyata kusadari komposisi anggotanya yang heterogen. Anggotanya datang dari beragam latar belakang profesi, seperti juru bahasa, editor, penerbit, production house, departemen pemerintahan, kantor berita, televisi, penerjemah di kedutaan besar negara asing, agen penerjemahan, dokter, ahli hukum, ekonom dan banyak sekali yang lain. Banyak juga penerjemah asing dari berbagai negara yang turut bergabung. Semua topik dibahas dengan semangat asah, asih, asuh begitu menarik, ditambah adanya bermacam-macam informasi yang menambah wawasan penerjemahan.
Aku juga mendaftar sebagai anggota biasa Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Beberapa temanku yang masih pemula terdaftar sebagai anggota muda. Ada kegiatan menarik yang kami lakukan beberapa bulan sekali, seperti pelatihan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penerjemahan dan kejurubahasaan atau sekadar temu darat untuk berbagi pengalaman.
Sebenarnya untuk mempertinggi kualitas diri dan meyakinkan klien, banyak juga ujian atau sertifikasi yang bisa diikuti penerjemah, misalnya saja Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP). Ujian ini dibagi menjadi dua, yaitu terjemahan umum dan terjemahan hukum. Peserta yang lulus dalam ujian terjemahan umum akan mendapatkan sertifikat sebagai certified translator. Jika ingin mendapatkan SK Gubernur DKI sebagai penerjemah bersumpah (sworn translator), maka yang harus diikuti adalah ujian terjemahan hukum. Sayang ujian yang diselenggarakan setahun sekali ini hanya dibuka untuk peserta yang memiliki KTP Jabotabek. Mengingat persyaratan kelulusannya sangat ketat, maka persentase peserta yang lulus juga sangat kecil.
Tes Sertifikasi Nasional (TSN) yang diadakan Himpunan Penerjemah Indonesia Tesjuga dapat diikuti semua penerjemah anggota HPI di seluruh Indonesia (tidak hanya dibatasi warga Jabotabek). Walaupun sebenarnya materi soal juga tak kalah sulit dibandingkan UKP, namun waktu pelaksanaan tes berlangsung setahun dua kali.
Setelah semua perbekalan keahlian siap, Tes kemampuan memasarkan diri juga harus kutingkatkan. Ibarat pepatah,tak kenal maka tak sayang. Meskipun kita benar-benar mumpuni, tetapi jika kita tetap bersembunyi, maka calon klien tidak melihat kita. Semakin pintar memasarkan diri, pekerjaan yang datang bahkan tak menutup kemungkinan berasal dari luar negeri dengan tarif Dolar atau Euro.
Perjuangan menjadi seorang penerjemah memang tak mudah. Selain kemampuan menerjemahkan, kepiawaian diri kita untuk menjaring relasi dan memasarkan diri juga diperlukan. Harga atau rate menerjemahkan juga kubuat dengan “manusiawi”. Terkadang aku heran mengapapara penerjemah baru – yang karena ketidaktahuan mereka atau terdesak kebutuhan – menetapkan rate yang sangat rendah kepada klien internasional. Padahal yang patut diingat, mereka tidak sedang menghadapi klien dalam negeri, jadi seharusnya juga tidak menggunakan rate dalam negeri. Jika rate terlalu rendah, yang rugi adalah penerjemah itu sendiri dan sesama penerjemah yang lain. Biasanya untuk pasar internasional, rate manusiawi yang digunakan adalah USD 0.05/kata (lima sen per kata sumber). Sedangkan untuk pasar domestik, pada tahun 2005 HPI mengeluarkan acuan yang bisa dilihat di situs HPI atau blog Bahtera. Namun karena itu hanya acuan, penerjemah boleh saja menaikkan atau menurunkan tarifnya dari daftar yang ada, tergantung kesepakatan dengan klien.
Hal-hal di atas tersebut niscaya sudah diketahui oleh para penerjemah profesional, dan sebetulnya masih banyak lagi kiat lainnya. Dunia penerjemahan ini sangat luas, dan yang sempat kujelajahi baru seujung kukunya.
Belum lama ini aku bertemu dengan mantan bosku. Ia bertanya, “Jadi apakah seluruh keinginan Mbak dengan menjadi penerjemah penuh waktu sudah terpenuhi?”
“Sebagian besar sudah. Tapi saya salah tentang satu hal. Ternyata saya tidak dapat libur apalagi mengambil cuti panjang semaunya meskipun sudah menjadi freelancer, dan jam kerja tanpa lembur itu pun hanya angan-angan.”


Tinggalkan komentar